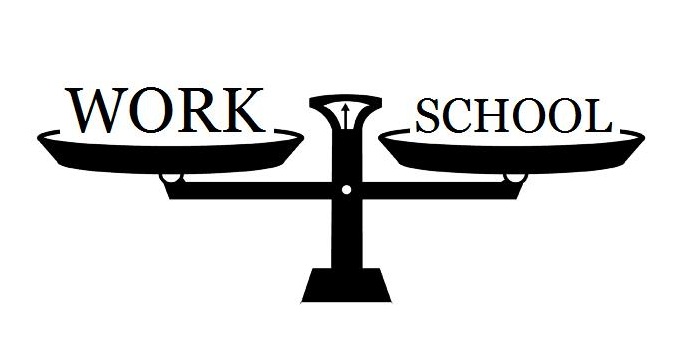 |
| Sumber gambar: http://moneymindedlearning.com/ |
Ya, saya memang suka
sekolah. Saya sekolah umur lima tahun. Umur 11 tahun saya lulus SD. Saya melanjutkan
ke Mts dan aliyah, dengan sekolah di pesantren juga. Enam tahun saya belajar di
pesantren. Setelah itu saya kuliah di Jakarta dan tinggal di asrama mahasiswa
yang juga mirip pesantren. Di tahun akhir kuliah saya, saya mendaftar kuliah
lagi dengan beasiswa. Tak tanggung-tanggung, kuliahnya jurusan islamic studies
yang banyak membahas filsafat. Tahun kelima saya lulus kuliah dan masih
melanjutkan kuliah rangkap saya. Sayangnya, kuliah kedua saya ini tidak selesai
dan berhenti di proposal skripsi. Berhenti satu tahun dari bangku sekolah
formal, saya mendaftar S2 di UIN Jakarta, meskipun saat itu saya sudah menikah
dan harus tinggal terpisah di dua kota dan pulau yang terpisah. Tiga tahun saya
menyelesaikan kuliah S2 saya dan saya lulus cumlaude. Sekarang pekerjaan saya
menjadi ibu rumah tangga.
Jadi, sekolah selama itu
ujung-ujungnya hanya di rumah saja? Ngabis-abisin duit saja. Itu mungkin
pandangan banyak orang, temasuk pandangan salah seorang kerabat saya tersebut. Ada pula pandangan orang tua yang menurut saya
anehnya luar biasa. ‘Keluar duit banyak untuk nyekolahin anak yang belum tentu
pekerjaannya itu merugikan. Mending keluar duit buat ngelamar kerja yang
terjamin (menyuap untuk PNS, maksudnya).’
Belajar untuk bekerja. Mungkin
itulah pandangan masyarakat pada umumnya. Kalau sudah belajar (sekolah, maksdunya)
ya harus bekerja (bekerja pada orang lain, bekerja di kantor, bekerja di
pabrik, khususnya). Kalau tidak bekerja, sia-sialah ilmunya. Juga sia-sia
duitnya.
Itu pandangan banyak orang.
Karenanya ada istilah sarjana nganggur. Konon angka pengangguran dari kalangan
sarjana dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena saya tidak bekerja (di
kantor), saya mungkin dimasukkan dalam statistik tersebut. Tidak apa-apa. Ibu rumah
tangga memang masih tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan (karena tidak
bergaji).
Apakah saya sedih dianggap
sarjana menganggur? Apakah saya tersinggung dengan sindiran sang kerabat (dan
mungkin juga masyarakat lainnya)? Tidak. Karena ajaran yang saya terima sejak
kecil dari ibu dan abah saya adalah belajar untuk memupuk keimanan, belajar
untuk bahagia dunia dan akhirat, belajar untuk lebih mendekatkan diri pada-Nya,
bukan sekadar untuk pekerjaan dan duit.
Anda boleh saja bilang saya
naif dengan alasan-alasan saya. Tidak apa-apa. Tapi kecintaan belajar saya
sejak kecil hingga kini memang tidak saya niatkan untuk melulu mendapatkan
pekerjaan. Anda mungkin bertanya, memangnya saya tidak butuh pekerjaan yang
menghasilkan uang? Ah, siapa sih di dunia ini yang tidak butuh duit. Saya pun
butuh duit untuk hidup. Saya pun pernah bekerja banting tulang untuk kehidupan
saya. Mulai dari guru privat, guru ngaji, menjadi wartawan, editor buku,
penulis (meski cuma satu buku), sampai sekarang ini saya berdagang
kecil-kecilan dari rumah. Dari semua pekerjaan itu, hanya beberapa jenis
pekerjaan saja yang berhubungan dengan jurusan kuliah saya, yaitu guru ngaji. Itu
saja. Ilmu jurnalistik saya dapat dari pengalaman mengelolah lembaga pers
kampus zaman kuliah. Berlanjut pada editor buku dan penulis. Lalu apakah ilmu
yang saya pelajari bertahun-tahun sia-sia karena saya tidak bekerja?
Saya berani katakan tidak. Ilmu
dari pesantren membekali hidup saya, bahkan hingga saat ini. Saya jadi tau
thaharah dengan benar dan saya jadi sangat berhati-hati akan masalah ini
(karena itulah saya tidak memperkerjakan asisten rumah tangga yang belum tentu
kenal najis). Saya tau aqidah dan ilmu kalam yang membekali saya dalam bersikap
terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Saya tau ilmu nahwu shorof (meski
banyak yang lupa) yang memudahkan dalam membaca kitab suci. Saya mengenal
tasawuf dari almarhum guru saya yang menjadikan saya seperti sekarang
(bukan...bukan sufi), pokoknya seperti ini lah.
Kalau dari awal saya
niatkan sekolah untuk bekerja dan mendapatkan gaji, saya tidak akan kuliah di
IIQ, kampus khusus perempuan yang oleh pendirinya didirikan untuk mencetak
calon ibu yang akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Saya akan kuliah di
jurusan ekonomi, hukum, atau sekalian kedokteran. Kalau saya menganggap sekolah
hanya melulu untuk bekerja dan mendapatkan duit, saya tidak akan kuliah
rangkap, jurusan filsafat Islam pula. Untuk apa sibuk belajar filsafat, toh
tidak ada perusahaan yang membutuhkan seorang filosof untuk diangkat menjadi
karyawannya.
Nah, alasan saya mengambil
S2 memang ada sisi-sisi praktisnya. Suatu saat saya ingin menjadi dosen. Karenanya
saya harus S2. Saya ingin berbagi ilmu saya. Syukur-syukur kalau mendapatkan
duit. Kalau kesempatan belum ada dan keadaan belum memungkinkan, saya
manfaatkan ilmu saya dengan mengajar anak-anak saya, mengajar TPA (yang
seringkali diremehkan orang dengan tenaga pengajar seadanya), dan ngajar les di
rumah saya. Saya tidak merasa merugi waktu dan biaya atas semua proses panjang sekolah
yang saya lalui (jika ditotal, saya sekolah sejak umur tiga tahun sampai umur
dua puluh delapan). Masing-masing jenjang persekolahan telah banyak mengajarkan
ilmu yang membentuk kepribadian saya, bukan sekedar pengetahuan dan
ketrampilan.
Agaknya kita harus memahami
klasifikasi ilmu aga kita tidak salah faham terhadap ajaran Nabi tentang
wajibnya menjadi ilmu. Dalam klasifikasi ilmu ini, saya setuju dengan klasifikasi
Imam al-Ghazali yang membagi ilmu pada dua kategori, yaitu ilmu fardhu ‘ain dan
ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ‘ain (singkatnya) adalah ilmu yang wajib
diketahui, dimiliki, dan diamalkan oleh setiap individu muslim sebagai syarat
tercapainya status kemuslimannya. Prinsipnya,
‘segala sesuatu yang menjadikan sesuatu itu wajib, maka ia dengan sendirinya
wajib.’ Seorang muslim harus mengenal Tuhannya, karena itulah wajib baginya
mengetahui ilmu aqidah. Seoarng muslim wajib menjalankan sholat, karena itulah
dia wajib mengetahui ilmu fiqh, tasawuf, akhlak, dan ilmu-ilmu lain yang terkait
dengan sholat. Seorang muslim harus berakhlak baik, karena itulah dia wajib
mengetahui ilmu akhlak.
Ilmu fardhu ‘ain ini
berkaitan dengan keimanan dan kewajiban-kewajiban individu terhadap keimanannya
tersebut. Ini terkait dengan jiwa. Pada akhirnya, ilmu ini akan membentuk
pandangan hidup dan menjadi pondasi bagi ilmu fadhu kifayah yang besifat
partikular, berubah-ubah, fisik, dan sosial.
Sementara ilmu fadhu
kifayah adalah ilmu-ilmu pilihan. Singkatnya, ilmu ini terkait dengan profesi. Tiap
individu berbeda kapasitas kemampuannya. Ada yang mempunyai kemampuan di bidang
kedokteran, ada pula di bidang ekonomi, hukum, tata negara, politisi, pedagang,
pekerja pabrik, seniman, mufassir, pendakwah, ahli fatwa, guru, dan lain-lain.
Kedua ilmu tersebut
sejatinya tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus bersinergi dan menjadi satu
kesatuan dalam pribadi setiap muslim. Kendati mempunyai kedudukan yang berbeda
(ilmu fardhu ‘ain lebih tinggi dari ilmu fardhu kifayah), keduanya bersifat
fardhu (wajib). Artinya, tiap muslim harus mencaiapnya.
Nah, apa hubungan pembagian
ilmu dengan tema di atas? Begini, bolehlah sekolah diniatkan untuk mencari
kerja. Boleh pula belajar diniatkan untuk mencari duit. Tapi dalam ajaran kita,
ada hal lain yang lebih penting dari sekedar kerja dan duit yang harus
dijadikan tujuan utama belajar, yaitu tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi
tujuan utama belajar, sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya, atau
bahkanyang tidak berlembaga seperti homeschooling, adalah untuk menjadikan
anak-anak sebagai seorang hamba Tuhan yang menyembah (secara benar) kepada-Nya,
baik kepada sesama, berakhlak mulia, dan cinta alam semesta. Nah, baru setelah
itu anak diarahkan sesuai passionnya.
Ketika ilmu-ilmu fardhu ain telah menjadi jiwa anak, mau jadi apapun dan mau
jadi siapapun, si anak akan tetap memiliki jiwa dan spiritualitas yang baik. Ketika
jadi pemimpin, maka ia akan jadi pemimpin yang amanah. Ketika jadi dokter, maka
ia akan jadi dokter yang jujur. Ketika jadi guru, ia akan jadi guru yang tulus.
Pun ketika jadi ibu rumah tangga, ia akan menjadi ibu rumah tangga yang amanah
terhadap titipan-Nya (anak-anak), taat pada kebaikan suaminya, dan peduli pada
lingkungan sekitarnya.
Yang terakhir inilah doa
terdalam yang selalu saya panjatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar